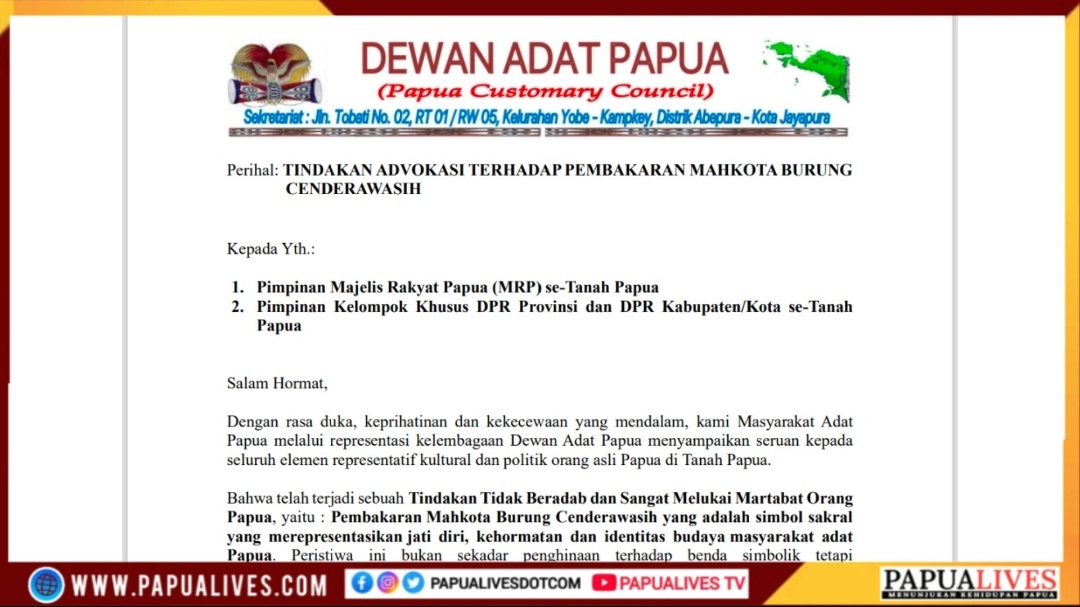Oleh Thomas Ch. Syufi*
Minggu, 19 Oktober 2025, dari balik rimba Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, berembus kabar duka nasional yang mengejutkan seantero masyarakat Papua atas meninggalnya pimpinan kombatan Tentara Pembebasan Nasional Papua-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Komando Daerah Pertahanan (Kodap) XV Ngalum Kupel Brigadir Jenderal Lamek Taplo karena serangan bom menggunakan drone oleh Tentara Nasional Indonesia. Kepergian salah satu pentolan berpengeruh dalam tubuh TPNPB-OPM di saat masyarakat Papua masih bergelayut duka atas terbunuhnya 12 warga sipil dan tiga militan TPNPB-OPM di Kampung Soanggama, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, 15 Oktober 2025 ini tidak hanya menyisakan kesedihan mendalam, tetapi juga meninggalkan beragam kisah heroik dalam perjuangannya untuk mewujudkan keadilan, kebenaran, dan perdamaian di Tanah Papua.
Tidak hanya Lamek Taplo, tiga anak buahnya pun ikut gugur dalam serangan udara paling mematikan di wilayah yang menurut sebagian pihak jaraknya berdekatan dengan pemukiman penduduk sipil (sebagai tempat beraktivitas seperti berburu hewan dan berkebun masyarakat Kiwirok). Di mana, Pegunungan Bintang merupakan salah satu daerah di Papua yang kurun empat tahun terakhir dilanda konflik bersenjata parah antara militer Indonesia dan TPNPB-OPM. Konflik ini menyebabkan 264 warga sipil mengungsi dari Distrik Oksop ke Distrik Oksibil, termasuk 54 balita, 23 lansia, 5 ibu hamil, dan dua pasien berat. Pengusian itu terjadi karena pihak militer masuk menguasai daerah Distrik Oksop, untuk mengejar para kombatan TPNPB-OPM (Laporan, SKPKC Fransiskan-Papua dan GIDI Papua, BBC, 13 Desember 2024).
Sampai saat ini, sejumlah sumber menyebut bahwa masyarakat yang menjadi korban konflik di daerah Pegunungan Bintang masih berada di daerah pengungsian, sama halnya beberapa daerah konflik lain di Tanah Papua, seperti Nduga (Papua Pegunungan), Intan Jaya (Papua Tengah), dan Maybrat (Papua Barat Daya) yang menambah total jumlah pengungsi warga sipil di Papua mencapai sekitar 76.228. “Permintaan masyarakat pengungsi, militer yang saat ini mengusai Oksop harus ditarik keluar baru masyarakat berani kembali ke kampung,” kata seorang biarawan Fransiskan sekaligus aktivis SKPKC FP (BBC, 13 Desember 2024). Jadi, para pengungsi di daerah konflik di Tanah Papua, termasuk Pegunungan Bintang sampai saat ini belum pulih dari trauma dan ketakutan yang luar biasa karena kehadiran militer yang terlalu berlebihan di kampung atau distrik mereka, dengan menggunakan kelengkapan peralatan perang seperti senjata dan helikopter milik militer, yang mempertebal rasa ketakutan warga sipil di sana.
Inilah salah satu dampak buruk krisis kemanusiaan di Tanah Papua yang lahir dari konflik 60-an tahun antara negeri ini dan pemerintah Indonesia. Resistensi rakyat Papua yang konsisten terhadap pemerintah Indonesia itu berangkat dari beberapa hal mendasar, seperti kekecewaan historis dan pelanggaran hak asasi manusia yang masif tanpa penyelesaikan yang adil, jujur, koprehensif, dan tuntas oleh negara. Presiden Soekarno memberlakukan Tri Komando Rakyat (Trikora) 19 Desember 1961, yang salah satu poinnya menunutut dibubarkan “negara” boneka (Papua) bikinan Belanda. Selanjutnya dibuatkan Perjanjian New York (New York Agreement) 15 Agustus 1962 tanpa keterlibatan wakil resmi rakyat Papua di dalamnya, hingga kesepakatan ini dianggap oleh mayoritas rakyat Papua cacat formil dan materil. Lalu, penyerahan Irian Barat dari pemerintah Belanda kepada UNTEA (Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB) pada 1 Mei 1963, menurut Pasal 2 Perjanjanjian New York yang dianggap ilegal itu untuk mengelola bekas koloni Belanda, Irian Barat. Atau tujuan Perjanjian New York 15 Agustus 1962 ialah penyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda atas status politik bangsa Papua, dengan diberikan kesempatan kepada oran asli Papua untuk menentukan nasibnya sendiri (Socrates Yoman, 2022).
Dan dilaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) atau referendum tahun 1969 sebagaimana termuat dalam Pasal 14-21 Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang mengatur tentang self determination (penentuan nasib sendiri) harus dilakukan menurut prinsip dan mekanisme internasioal, yaitu salah satunya, “one man, one vote” (satu orang, satu suara). Masalahnya, Pepera yan digelar antara tanggal 14 Juli sampai 02 Agustus 1969 di mana 1.025 orang yang dipilih oleh militer Indonesia di Irian Barat memberikan suara bulat untuk bergabung dengan Indonesia. Intrik, manipulasi, intimidasi, dan teror mewarnai hari-hari plebisit dilangsungkan di seluruh Tanah Papua.
Pelangaran HAM di Papua sudah begitu lama sejak tahun 1960-an tak pernah terselesaikan. Baik itu di Manokwari, Sorong, Merauke, termasuk Biak berdarah 1998, Abepura berdarah 2000, Wasior berdarah 2001, Wamena berdarah 2003, Abepura berdarah 2006, penembakan Opinus Tabuni 2009, pembunuhan Mako Tabuni 2012, Paniai berdarah 2014, pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani 2019, dan penembakan 14 orang di Intan Jaya 15 Oktober 2025 yang diduga 12 orang di antaranya adalah warga sipil dan sisanya milisi TPNPB-OPM (Tempo, 16/10/2025).
Karena persoalan sejarah penyatuan politik Papua dalam NKRI dan ketidakadilan berupa pelangaran hak asasi manusia di Tanah Papua menjadi alasan paling fundamental yang memicu berbagai gejolak di Tanah Papua. Pemerintah Indonesia tampak tidak menghirauan aspirasi masyarakat Papua yang menuntut agar sejarah integrasi Papua ke Indonesia harus diklarifikasi melalui jalan dialog atau pelurusan sejarah. Juga, dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan Pengadilan HAM ad Hoc sesuai amanat Pasal 45 Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, untuk mengungkap kebenaran, mendorong keadilan retributif/pengadilan terhadap pelaku kejahatan HAM, dan melakukan rehabilitasi korban pelanggaran HAM, serta rekonsiliasi untuk pelaku dan korban pelanggaran HAM masa lalu.
Namun, sampai saat ini apa yang dinormakan dalam regulasi otonomi khusus Papua ini belum terealisasi dan terkesan pemerintah pusat tidak mempunyai itikad baik untuk melaksankan Undang-Undang Otsus secara murni dan konsekuen. Sudah lebih dari 20 tahun kebijakan Otsus diimplementasikan di Papua, namun belum maksimal bahkan nyaris nihil dalam penerapannya. Otsus hanya indah kabar daripada rupa. Otsus belum memberikan dampak signifikan dari aspek proteksi, afirmasi, dan pemberdayaan terhadap Orang Asli Papua (OAP).
Atas absennya negara memberikan keadilan bagi orang Papua dalam berbagai aspek kehidupan, ini secara otomatis negara sendirilah menjustifikasi dan melanggengkan konflik di Papua. Ini merupakan konflik struktural dan laten di Tanah Papua yang sengaja dilestarikan oleh negara melalui proses pembiaran dan pengabaian terhadap tuntutan masyarakat Papua, termasuk kelompok kombatan TPNPB-OPM. Esensi tuntutan mereka jelas: negara harus menyelesaikan semua persolan di Tanah Papua secarah holistik dan menyeluruh, terutama pelurusan sejarah politik Papua dan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran HAM berat di masa lalu tanpa impunitas. TPNPB-OPM meyakni bahwa Otonomi Khusus adalah sebuah kebijakan politik untuk meredam aspirasi Papua merdeka, bukan panduan imperatif teoritis, maka Otsus tidak mungkin sukses dilaksanakan dalam Negara Kesatuan, karena segala kendali penyelenggaraan pemerintahan tetap sentralistik.
Dengan segala kegagalan pemerintah pusat dalam menyelesaikan konflik Papua melalui jalan keadilan dan dialog dapat memicu eskalasi konflik di Bumi Cenderawasih, terutama konfrontasi bersenjata antara kelompok TPNPB-OPM versus TNI/Polri. Tuntutan kelompok bersenjata di Papua, tentu termasuk Lamek Taplo (alm) itu gamblang, yakni perlu pemerintah Indonesia merundingkan dengan mereka terkait status politik Papua dalam skema NKRI yang masih kontraversial sampai saat ini. Juga semua pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu harus dibawa ke mimbar hukum, diadili dan dihukum setimpal kejahatan mereka (culpae poena par esto). Inilah inti permasalahan yang terjadi di Papua, bukan sebaliknya pemerintah pusat mengirimkan pasukan militer dan memamerkan peralatan tempur yang berlebihan, melakukan operasi militer besar-besaran dan melakukan kekerasan terhadap warga sipil di berbagai tempat di Tanah Papua. Kekerasan tidak bisa menyelesaikan kekerasan, tetapi justru membuat situasi kian runyam, dapat mengancam kondusivitas keamanan dan memperburuk situasi hak asasi manusia di Tanah Papua. Kekerasan juga merupakan bentuk lain dari kolonialisme yang harus disingkirkan dari negara demokrasi, yang menjujung tinggi hak asasi manusia dan supremasi sipil. Karena itu, perjuangan Brigadir Jenderal Lamek Taplo dan kedua pasukannya yang gugur di medan perjuangan menuntut keadilan, kebenaran, dan perdamaian, perlu diapresiasi, meski jalan perjuangan yang ditempuhnya mungkin tidak disukai oleh kebanyakan orang. Semangat, cita-cita, dan integritas perjuangan mereka sangatlah penting, menjadi kompas moral yang memandu perjalanan generasi bangsa ini ke depan untuk memperjuangkan kebaikan bersama (bonum commune).
Tentu sebagian orang memandang cara perjuangan bersenjata yang dilakoni oleh Lamek Taplo maupun para pendahulu lainnya, seperti Permenas Fery Awom, Johanes Kaprimi Jambuani, Kelly Kwalik, Bernard Mawen, Richard Joweni, Matias Wenda, dan Matias Tabu, memang sukar dan tidak bisa memecahkan persoalan. Tetapi bagi mereka, revolusi dapat dicapai bisa hanya melalui perang gerilya, sama halnya bagi seorang misionaris revolusi dapat dicapai bisa hanya melalui lantunan doa yang penuh kontemplatif, bagi seorang musisi revolusi bisa dicapai melalui kutikan guitarnya, bagi seorang diplomat revolusi dapat dicapai melalui seni berdiplomasi, bagi aktivis perdamaian revolusi hanya bisa diraih melalui dialog, dan bagi aktivis demokrasi, revolusi hanya direbut melalui gerakan “people power”. Kesemunya memiliki satu tumpuan, yaitu mewujudkan keadilan dan perdamaian, meski jalan yang diambil tentu berbeda, penuh rintangan, dan risiko, juga terjadi silang pendapat secara internal maupun eksternal dari setiap komunitas perjuangan.
Bagi aktivis perdamaian dan demokrasi, perdamaian hanya bisa diwujudkan melalui jalan penegakan keadilan, atau si vis pacem para iustitiam, jika mengindamkan perdamaian siapkan keadilan. Karena pada hakikatnya tiada perdamaian tanpa keadilan. Keadilan menjadi unsur primer bagi tegaknya perdamaian, maka keadilan diberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (justitia est ius suum cuique tribuere). Namun, bagi para gerilyawan, mungkin juga termasuk Lamek Taplo, memandang bahwa perdamaian dan keadilan tidak mungkin datang dengan cuma-cuma tanpa ada desakan atau paksaan melalui kekuatan senjata, si vis pacem para bellum, jika menginginkan perdamaian, persipkanlah perang. Meminjam “Che” Guevara, ”Revolusi bukanlah buah apel yang akan jatuh saat ia matang, kau harus membuatnya jatuh”. Lantaran, tujuan akhir dari perang adalah mewujudkan kesepakatan damai bersama antara para pihak yang terlibat bentrok senjata.
Karena itu, jawaban untuk mengakhiri gejolak berkepanjangan (longstanding/prolonged unrest) di Tanah Papua adalah mewujudkan keadilan, dengan dilakukan pelurusan sejarah status politik Papua dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. TNI/Polri dan TPNPB-OPM bisa mengambil opsi terbaik dan bermartabat untuk menghentikan pertumpahan darah dan litani kematian di Tanah Papua dengan melakukan perundingan, yang diawali cessation of hostilities (penghentian permusuhan), bukan truce (gencatan senjata informal), tetapi gencatatan senjata secara formal (ceasefire), yang dapat melahirkan solusi permanen demi mewujudkan Papua tanah damai. Karena selama 60-an tahun Papua menjadi bagian dari Indonesia, angggpan TPNPB-OPM bahwa yang dalang di dari konflik bersenjata di Papua adalah pemerintah Indonesia. Tentu saja anggapan TPNPB-OPM, we are peacemaker, but you are a warmonger (kami adalah pembawa damai, tapi kamu adalah penghasut perang) yang membuat orang Papua menderita sepanjang waktu dan membuat Papua seperti ladang pembantaian (killing fields) atau Papua is slaughterhouse (Papua adalah rumah pembantaian/tempat penumpahan daarah).
Mungkin dalam benak sebagian masyarakat Papua bahwa kini, Brigadir Jenderal Lamek Laplo telah pergi untuk selamanya, tetapi jiwa dan dedikasi perjuangannya akan selalu dikenang dan dihormmati sekaligus dipelihara rakyat di negeri ini, terutama generasi muda. Sebagai bekal dalam usaha-usaha untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian di Tanah Papua melalui beragam cara, terutama dialog jujur dan bermatabat. Taplo adalah seorang kombatan militan yang konsisten pada pilihan hidupnya, ia mengambil jalan yang paling sulit dan tidak disukai oleh kebanyakan orang Papua. Bagi Lamek Taplo, Kelly Kwalik, Theys Hiyo Eluay, Tom Beanal, Tom Wanggai, John Mambor, Arnold Ap, Victor Kaisiepo, Leonie Tanggahma, John Otto Ondawame, Andy Ayamiseba, Mako Tabuni, dan Filep Karma hanya satu pilihan: tanah air atau mati (patria o muorte). Mereka adalah orang-orang yang berjuang tanpa pamrih di berbagai medan perang, diplomasi, dan politik. Mereka tidak memikirkan kebahagiaan dan kenikmatian diri dan keluarganya, juga tidak membayangkan apa yang didapat kelak setelah perjuangannya untuk revolusi tercapai. Karena perjuangan untuk sebuah kebenaran dan keadilan, tidak selamanya dituntaskan dalam satu generasi, tetapi akan berlangsung lama, lintas waktu, dan zaman, maka estafet perjuangan pun secara bergiliran akan mengalami pergantian dari generasi ke generasi.
Bagi mereka, tidak penting siapa yang mengakhiri perjuangan ini, tetapi yang lebih utama adalah api perjuangan tetap berkobar dari satu generasi ke generasi berikutnya tanpa diinterupsi dengan keputusasaan, sinisme, dan pesimisme yang kini menyebar di seluruh Tanah Papua, yang kita menyadari bahwa di sekitar kita kini, dulu, maupun nanti, selalu ada tak terhitung orang yang sepenuhnya tulus bekerja dan berjuang demi kebaikan sesama dan masa depan Tanah Papua. Mereka adalah orang-orang hidup dalam kredo, mendedikasikan seluruh hidupnya untuk berjuang, membela, dan merawat keyakinan akan nilai-nilai kebaikan bersama tanpa mengeksplisitkan syahadat mereka.
Kata kredo yang dipahami secara universal dalam KBBI sebagai “dasar tuntutan hidup”, atau oleh Merriam-Webster, a guiding principle. Keduanya mengacu pada keluhuran manusia atau bangsa. Bercita-cita luhur, orang-orang berkredo menjunjung kemanusiaan dengan terus memelihara kemurnian amal. Tak selalu menonjolkan kredo mereka, tetapi mereka dituntun oleh dasar dan prinsip luhur. Hidup mereka sarat kebajikan dan perjuangan. Mereka sadar dan tulus memilih berbakti kepada sesama melampaui batas-batas perbedaan tanpa mencari sensasi. Serta altruisme perjuangan mereka untuk kepentingan tanah air di tengah tantangan berat maupun kesunyian, kebencian, serta taruhan nyawa. Mereka berjuang tanpa merendahan diri demi posisi dan materi (Mochtar Pabottingi: Kompas, Kamis, 4 Juni 2015).
Tanpa mengagitasi atau memprovokasi siapa pun untuk mengambil jalan perang sebagai solusi penyelesaian masalah, membela kemanusiaan dan tanah air, tetapi ini sekadar ungkapan perasaan glorifikasi ksatria dan heroisme para perjuang yang berani mengambil jalan penuh risiko di pedan perang lalu gugur, termasuk Brigjen Lamek Taplo dan kedua anggotanya yang tewas karena serangan udara militer Indonesia di Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Mengutip ungkapan terkenal dari puisi Romawi kuno oleh penyair Quintus Horatius Flaccus (65-8 SM): “Dulce et decorum est pro patria mori (hal yang manis dan mulia apabila seseoran mati atau gugur untuk negeri/tanah airnya). Peace be with all of you (semoga damai menyeratai kalian semua). Liberte.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
*) Penulis adalah Advokat dan Direktur Eksekutif Papuan Observatory for Human Rights (POHR).